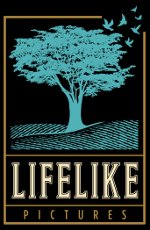Kisah Manusia dari Tabula Rasa

Oleh: Nuran Wibisono
Kemarin malam akhirnya saya bisa menonton Tabula Rasa. Film ini sudah menarik rasa penasaran saya kala trailernya berseliweran di linimasa Twitter beberapa waktu lalu. Jarang ada film Indonesia yang berkisah tentang kuliner. Seingat saya baru Brownies yang melakukannya. Itu pun lebih banyak berkisah tentang drama cinta.
Tapi Tabula Rasa berbeda. Dalam trailernya, jelas kalau film ini berkisah tentang kuliner Minang. Dan kala sebuah film mengangkat kuliner sebagai tema sentral, maka mustahil untuk abai terhadap kisah manusianya. Karena film tentang makanan pasti berkisah tentang manusia. Makanan, gastronomi, adalah karya adiluhung manusia.
Di belahan dunia lain, ada banyak film luar biasa bagus mengenai kuliner. Mulai Big Night, Tampopo, Eat Man Drink Woman, Soul Kitchen, The God of Cookery, Tonight’s Special, Mostly Martha, hingga Jadoo King of Curry. Semua selalu berkisah soal manusia. Kisah makanan ini juga menerabas genre film. Komedi ada. Drama ada. Thriller juga ada.
Makanya sangat disayangkan kalau di Indonesia belum ada film bagus soal makanan. Padahal siapa yang bisa menyangkal keberagaman kuliner di Indonesia?
Keberagaman juga menjadi benang merah yang menjalin cerita Tabula Rasa. Film besutan Adriyanto Dewo ini mengisahkan tentang Hans, seorang pemuda asal Serui, Papua, yang punya bakat dalam sepak bola. Suatu hari ia diundang untuk bermain di sebuah klub bola asal Jakarta. Ia pun memutuskan untuk berangkat ke ibu kota. Tapi di sana semua mimpi Hans hancur lebur. Kakinya patah. Klub tak mau bertanggung jawab.
“Mereka membuang saya seperti sampah,” katanya.
Hans pun jadi gelandangan. Mengumpulkan ceceran beras untuk ditukar dengan uang receh. Hanya cukup untuk beli tempe goreng. Hans kumel. Jarang mandi. Bajunya sobek-sobek. Suatu hari Hans berniat bunuh diri. Tapi ia terpeleset dan jatuh pingsan. Lantas ia ditemukan oleh Mak, seorang pemilik lapau Padang bernama Takana Juo.
Sejak itu jalan hidup Hans berubah. Ia bertemu dengan Uda Parmanto, juru masak Takana Juo; dan Natsir, pelayan Takana Juo. Di pertengahan kisah, Hans mulai belajar memasak masakan Padang. Mak dengan senang hati mengajari resep andalannya. Mulai dendeng batokok hingga gulai kepala ikan.
“Masak gulai kepala ikan ini seperti ziarah bagi Mak. Hans janji ya, kalau masak gulai kepala ikan juga harus menganggap ini sebagai ziarah,” kata Mak pada Hans yang berdiri dan menyimak dengan takzim.
Menyaksikan Tabula Rasa juga menyaksikan kisah manusia. Betapa rasa itu universal. Makanan bisa menyatukan manusia. Tak peduli rasmu. Tak peduli apa agamamu. Makanan enak yang dimasak dengan cinta, bisa membuatmu tergugah. Seperti misalkan kala Hans pertama kali mencicipi gulai kepala ikan yang sama sekali asing baginya.
Saya puas menonton film ini, terlepas dari beberapa kekurangan teknis yang wajar belaka. Saya seperti diajak masuk ke dalam pasar oleh Mak. Diajari cara mengulek bumbu. Bagaimana memasak dan memperlakukan makanan. Mak seperti guru yang sangat baik, yang mengajari para penonton betapa pentingnya perhatian kecil pada makanan.
“Mahal sedikit tak apa lah, asal lamak (enak).”
“Lidah orang Minang itu nomer satu.”
“Masak rendang itu harus sabar.”
“Bisa pakai kompor gas, tapi hasilnya tak akan seenak kalau memakai kayu bakar.”
“Bawang impor ini lebih murah, tapi rasanya hambar. Bawang lokal ini lebih mahal, dan rasanya lebih tajam.”
“Kamu bingung kenapa bawang lokal lebih mahal ketimbang impor? Sama, Mak juga bingung.”
Penampilan Jimmy Kobogau juga sangat menghibur. Ia polos. Lucu. Celetukannya berulang kali membuat saya tertawa keras. Ramdan Setia yang berperan sebagai Natsir juga tampil lugas, jadi partner yang seimbang bagi Jimmy. Mereka berdua acap terlibat percakapan yang memancing gelak.
Belum lagi adegan memasak yang sukses membuat cacing di perut memainkan orkestra keroncong. Adegan paling sadis ya kala Mak membakar daging dendeng batokok. Dendeng yang berwarna cokelat pucat dengan aksen hitam hasil panggangan itu lantas diguyur lado hijau, alias sambal cabai hijau.
Biadaaaaabbbb!
Malangnya, film ini sepertinya kurang ramai penonton. Bisa jadi karena nyaris nihil bintang film terkenal. Tak ada nama yang familiar bagi penonton, terutama yang berusia muda. Jelas kalah jauh jika dibandingkan dengan film yang dirilis dalam waktu berdekatan dan bertabur nama bintang terkenal, seperti Haji Backpacker, misalnya. Padahal dari segi tema dan cerita, Tabula Rasa jauh lebih unggul.
Kemarin malam, pemutaran hari keempat, film ini hanya ditonton oleh 13 orang saja, termasuk saya dan Rani. Saya sengaja menghitungnya. Sayang sekali. Padahal film ini bagus.
Jadi saran saya: kalau film ini masih ada di bioskop terdekat dari tempat kalian, segeralah menonton. Sebelum film ini turun layar karena sepi penonton. []
Source: Jakartabeat