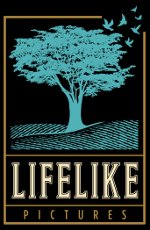Sheila Timothy: Pengembalian Modal Tidak Hanya dari Bioskop

oleh Pandji Putranda
Tabula Rasa adalah film ketiga produksi LifeLike Pictures dengan produser Sheila Timothy yang dirilis 25 September 2014. Disutradarai oleh sineas muda Adriyanto Dewo dan penulis Tumpal Tampubolon, film berdurasi 107 menit ini akan menghadirkan sebuah drama keluarga yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, sambil mengangkat kekayaan kuliner Indonesia sebagai poros cerita.
Sebagai produser, Sheila Timothy yang juga akrab disapa Lala menganggap Tabula Rasa bisa dibilang sebagai film kuliner pertama di Indonesia yang benar-benar memasukkan nilai-nilai sosial kuliner ke dalam ceritanya. Lebih dari itu, Tabula Rasa yang dalam bahasa latin berarti “kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, tanpa disertai prasangka” menjadi kesempatan bagi Lala untuk berkolaborasi dengan bakat-bakat muda baru di industri film nasional.
Sebelum Tabula Rasa, LifeLike Production telah memproduksi dua judul film yang disutradarai oleh Joko Anwar, yaitu Pintu Terlarang (2009) dan Modus Anomali (2012). Secara umum, genre film terakhir ini berbeda dengan dua film terdahulu.
“Saya mau membuat film yang (menurut saya) skripnya unik dan punya sesuatu yang beda untuk ditawarkan. Tidak ada pengkhususan diri ke genre tertentu. Atau mungkin kalau saya boleh cerita sedikit, ayah saya dulunya adalah seorang produser musik di tahun 70an. Dia selalu bilang ‘kalau mau jadi produser yang baik, jangan pernah menganaktirikan genre apapun’. Bagi ayah saya, semua musik pada dasarnya baik. Meskipun pada akhirnya akan ada penilaian pasar terhadap musik yang bagus dan musik yang kurang bagus. Dan menurut saya, cara pandang demikian juga dapat diterapkan pada film. Selama dikerjakan dengan baik dan memiliki skrip yang kuat, seharusnya sih bisa jadi film yang bagus.” tuturnya bersemangat.
Sekalipun tidak mengkhususkan diri pada genre tertentu, Lala mengaku dirinya sangat tertarik dengan cerita-cerita unik. Namun bukan berarti sok ingin tampil beda dari yang lain. Karena sebagai seorang produser, ia tentunya ingin membuat film yang diterima oleh penonton dari segmen yang dituju.
“Misalnya ketika membuat thriller bersama Joko Anwar, kami harus tahu pangsa pasarnya seperti apa. Namun kembali lagi, pada dasarnya saya memang suka dengan yang unik-unik. Karena menurut saya film Indonesia itu sudah banyak sekali. Dan saya bisa dibilang late bloomer –masuk sebagai produser di industri ini bisa dibilang telat. Apalagi di usia saya sekarang, produser-produser lain seangkatan seperti Mira Lesmana, Shanty Harmayn, sudah menghasilkan belasan sampai puluhan film. Sementara itu, melihat kondisi pasar Indonesia sekarang yang produksinya sudah seratusan film per tahun, saya merasa tidak ada gunanya membuat film yang mirip-mirip dengan yang sudah ada sebelumnya.”
Lala juga menambahkan ia lebih baik memproduksi satu film, namun digarap secara total dan terperinci, hingga pada akhirnya menjadi sebuah produk yang dalam versinya ‘nggak malu-maluin’.
Dalam Tabula Rasa, makanan digambarkan sebagai sebuah itikad baik untuk bersilaturahmi. Karena lewat makanan, setiap individu akan berbaur di dapur, saling memberikan harapan beserta semangat satu sama lain. Dan lewat kegiatan masak bersama pula, setiap individu berusaha untuk saling memahami dan meleburkan perbedaan-perbedaan yang ada.
Lala melihat ide atau gagasan utama atas film bertema kuliner ini memiliki potensi untuk diolah, dikembangkan, hingga nantinya disimak dan diterima oleh penonton Indonesia. Ia mengaku, kali pertama ide itu muncul ialah ketika malam-malam Lala tengah seru menonton program Asian Food Channel.
“Kemudian langsung terpikir, film Indonesia kok hampir tidak ada yang berbau kuliner ya? Begitu awal mulanya. Tapi kemudian saya pikirkan kembali, kalau nanti akan dibuat dalam format dokumenter, saya belum berani karena memang belum ada pengalaman di bidang itu. Lagi pula, menurut saya belum ada film Indonesia yang benar-benar mengambil sosial kuliner sebagai tema dasarnya, atau belum ada yang benar-benar food film. Kalaupun ada, beberapa yang pernah saya lihat lebih tepat disebut food porn ketimbang food film.”
Lala melanjutkan, “Saya pribadi lebih ingin nilai-nilai filosofis dari kuliner Indonesianya yang jadi sorotan. Ibarat rendang, dagingnya dari perwakilan pemuka agama, rempahnya dari perwakilan kelompok sosial A, dan seterusnya. Dengan begitu, masing-masing unsur akan memiliki cerita yang nantinya saling melengkapi. Bagian terkecil dari makanannya itulah yang merupakan poros utama cerita film ini.”
Awal Mula
Setelah ide kasar itu muncul, Lala mengajak Tumpal Tampubolon untuk menulis skrip pada tahun 2012. Walaupun sebelum mereka bertemu, Lala sempat membaca beberapa skrip karya Tumpal, dan memang sudah tertarik dengan gayanya bercerita. Lala mengakui bahwa Tumpal memiliki kemampuan mengolah sesuatu yang biasa-biasa saja menjadi menarik. Setelah mereka berbincang-bincang dan bertukar ide soal film ini, baru kemudian Tumpal mencoba menulis skripnya.
“Awalnya, seingat saya bukan antara Padang dengan Papua, tetapi Padang dengan Afrika! Jadi, ide utamanya adalah pemain bola dari Afrika. Alasan sederhananya, karena Tumpal mau menggambarkan perbedaan. Dan yang paling mudah ialah kekontrasan warna kulit lewat citra visual. Karena film itu kan visual. Tapi kemudian saya kasih masukan kalau Afrika itu cukup sulit. Maksudnya, saya sempat baca-baca soal Afrika dan menu makanan sampai bumbu masak mereka tuh berbeda jauh dengan Indonesia. Kendalanya banyak.” ujarnya terbahak.
“Setelah itu kami ngobrol panjang lagi, kemudian dia dapat ide lain. Nah, berhubung Tumpal punya profesor di ITB yang berasal dari Biak, namun tumbuh besar di Serui, dia sempat menyarankan tempat itu ke saya. Karena toh secara geografis, bagian Timur Indonesia yang lebih sering disorot adalah Wamena, Jayapura. Sedangkan banyak orang yang belum tahu tentang Serui. Setelah saya cari lewat Google, memang tempatnya lucu dan unik. Bayangkan, kampung kecil pesisir ditambah latar belakang kultural yang tidak kalah unik karena posisinya dekat dengan Makassar. Bahkan ada perkampungan Cina di sana yang biasa disebut Perancis, atau Peranakan Cina Serui.” jelasnya.
“Dari situ kami riset lagi, dan ternyata kami menemukan cukup banyak kesamaan dengan kultur Minang. Yang paling mudah contohnya, banyak di antara mereka yang sama-sama perantau di pulau Jawa. Dan kami rasa dua daerah ini cukup cocok untuk disandingkan. Kemudian, Minang mengenal gulai kepala ikan, sedang Serui mengenal ikan kuah kuning. Sekalipun secara resep keduanya berbeda, namun bahan dasarnya kan sama-sama ikan, sama-sama seafood. Jadi agak mirip-mirip lah.”
Setelah semakin yakin bahwa Serui adalah tempat yang menarik, Lala menyuruh Tumpal dan Adriyanto Dewo (sutradara) untuk langsung meninjau lokasi. Awalnya, tidak ada perencanaan sama sekali untuk syuting di Serui supaya menghemat anggaran. “Salahnya, setelah mereka kembali dari sana, mereka juga membawa pulang dokumenter pendek yang bagus luar biasa. Kurang ajar mereka!” Lala kembali terbahak. Singkat cerita, Tumpal dan Adri berhasil merayu Lala untuk melakukan pengambilan gambar di Serui, dengan alasan untuk memperluas pengetahuan penonton mengenai alam Indonesia bagian Timur.
Selain itu, karena anak-anak di Serui tinggal di rumah yang lebih dekat dengan sekolah, hingga pendidikan anak-anak di sana tergolong lebih baik dibanding Wamena yang jarak rumah-sekolah jauh. Bahkan banyak di antara mereka yang sering pergi pulang ke Makassar. “Dengan kata lain, bisa dikatakan lebih modern. Begitulah, karena saya tergoda dengan iming-iming Tumpal dan Adri, ditambah hasil riset kecil saya mengenai Serui, walhasil diputuskan syuting di sana. Ada sembilan adegan yang pada akhirnya diambil di Serui.” pungkas Lala.
Berbeda dengan Tumpal, Adri baru tergabung secara resmi dalam produksi Tabula Rasa setahun setelahnya, yakni pada 2013. Namun ini bukan kali pertama Lala bekerja sama dengan Adri. Sejak Modus Anomali, Adri sudah terlibat di bagian behind the scene. Beberapa kali Lala dan Adri bertukar cerita, membuat Lala berkesimpulan bahwa Adri ialah sosok yang menarik, pintar, memiliki jam terbang tinggi di dunia perfilman. “Saya suka sekali dengan gaya dia di Sanubari Jakarta (2012). Alasan lainnya, karena Adri memiliki pengalaman personal dengan kegiatan kuliner. Persisnya ketika ia dan keluarganya bisa sangat rukun ketika sedang memasak bersama.” lanjut Lala.
Namun begitu, Adri tetap masuk melalui jalur pitching. Ada tiga sutradara yang bersaing memperebutkan pitch, salah satunya Adri. Dan bagi Lala, Adri memiliki pendekatan yang paling cocok dengan skrip garapan Tumpal. Satu kalimat yang membuat Lala yakin memilihnya, yaitu ketika Adri bilang kalau film Tabula Rasa ialah sebuah film tentang kerinduan. Dan bicara soal kerinduan, pastinya ada unsur romantisme yang bersifat personal sekaligus nostalgik.
Perhitungan Komersil
Berstrategi di industri perfilman adalah salah satu tugas utama seorang produser film. Dengan asumsi bahwa Tabula Rasa merupakan film pertama Indonesia yang benar-benar mengangkat tema kuliner sebagai poros utama dan bukan sebagai hiasan visual belaka, LifeLike Pictures tentu sudah harus siap dengan segala perhitungan komersil. Mulai dari pangsa pasar, penjaringan sponsor, arus promosi, serta perimeter distribusi film tersebut.
“Proses yang kami lakukan kira-kira begini. Setelah saya mendapat ide dan saya lempar ke tim, kami sudah harus memikirkan seberapa besar target kami, yang secara otomatis akan memunculkan perhitungan bayangan mengenai seberapa besar kapasitas penonton Indonesia terhadap genre film yang akan kami produksi. Dari penghitungan kapasitas tadi, selanjutnya kami bisa mengkalkulasikan seberapa besar investasi yang masih masuk akal atau realistis. Nah, yang perlu diingat adalah ‘pengembalian modal tidak hanya berasal dari bioskop’. Jadi kami tidak membebankan film tersebut untuk sukses di pasaran dengan banyaknya jumlah penonton. Tidak demikian, karena menurut saya itu tidak realistis. Terlebih melihat kondisi (perfilman) kita sekarang ini.”
Ia melanjutkan, “Jadi saya bagi-bagi, dari bioskop berapa sih yang masuk akal? Dari televisi, mengingat film ini masuk kategori semua umur, berapa sih? Kemudian kami juga bisa masuk ke maskapai penerbangan –untuk pemutaran selama penerbangan berlangsung. Dan keuntungannya bisa berlipat ganda karena film kami mampu masuk ke wilayah lain. Tidak terbatas di Indonesia saja. Hal yang sama pernah terjadi di Modus Anomali. Dibantu oleh agen penjualan, kami bisa melakukan penjualan di berbagai negara, dan itu bisa jadi salah satu sumber untuk mengembalikan modal. Kemudian ada juga sponsor. Film Tabula Rasa sendiri adalah film semua umur yang bisa dikatakan ‘bersahabat’ untuk berbagai sponsor. Dan sponsor yang kami dapatkan sejauh ini sangat cukup untuk menanggung beban produksi. Sampai sekarang, kami sudah memiliki dua kandidat agen penjualan. Kita lihat saja nanti berhasil atau tidak. Kalaupun tidak, ada opsi lain seperti Malaysia dan Singapura dengan sistem pembagian keuntungan. Kami tinggal bawa ke sana, dan tinggal dibagi saja hasil keuntungannya.”
Menurut Lala, Tabula Rasa bisa dibilang ‘lebih mudah’ untuk dijual dibandingkan dua film Lifelike Pictures yang sebelumnya. Ia malah merasa heran bila ada yang menganggap film ini ‘susah’, karena sebetulnya tidak sama sekali. Banyak peluang yang terbuka dan dapat dimanfaatkan secara maksimal di film ini. Misalnya saja, dengan pembuatan desain kotak popcorn di 21. Dan karena film ini adalah film kuliner, tim LifeLike Pictures dapat masuk ke tiga komunitas sekaligus.
“Kami sudah gila-gilaan dengan banyak komunitas kuliner. Dari mulai masak bersama, mengadakan kegiatan kuliner bersama, terutama di banyak komunitas Padang. Karena sejujurnya mereka cukup fanatik dengan ke-Padang-annya. Bisa sembari promosi.” ujar Lala puas.
Bicara soal promosi, Tabula Rasa nampak melakukannya dengan cukup gencar. Kabar tentang film ini bahkan sudah mulai bermunculan di berbagai media sosial dari empat hingga lima bulan lalu. Mengingat banyak film Indonesia yang cukup lemah di departemen promosi, nyatanya Lala dan tim LifeLike Pictures sudah menyiasatinya dari jauh-jauh hari.
“Saya sendiri sempat bekerja di bidang periklanan sekitar tahun 90an, meski sebentar. Dan saya adalah seorang produser yang menganggap marketing dan promosi merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebab satu hal yang menjadi kekurangan di banyak film Indonesia adalah marketing dan promosinya tidak berjalan dengan baik. Buat film bagus, dilempar ke pasaran, tapi tidak banyak orang yang tahu. Buat apa? Nah, karena di Tabula Rasa, seperti yang saya bilang sebelumnya, punya lebih banyak peluang untuk melakukan promosi dan berjejaring dengan berbagai pihak eksternal, kami sudah membuat perencanaan marketing dan promosi dari tahun-tahun sebelumnya. Semenjak skrip mulai digarap, tim marketing juga sudah mulai bekerja dan melakukan perencanaan. Dan pelaksanaannya kami tunda dulu sampai pilpres berakhir. Karena kami rasa percuma juga kalau dijalankan di saat yang bersamaan dengan pilpres dan piala dunia, takut mubazir dan buang-buang tenaga. Maka dari itu, di bulan-bulan Agustus dan September inilah baru kami kerahkan secara maksimal. Mulai dari media partner, sponsor, dan lainnya, kami maksimalkan menjelang film ini rilis.” jelasnya bersemangat.
Keuntungan lainnya yang didapat melalui strategi di atas, LifeLike Pictures sudah memiliki anggaran promosi ketika mereka berhadapan dengan calon investor. Dengan demikian, perencanaan anggaran yang dilakukan tidak terbatas pada tahap pra dan produksi saja, promosinya pun sudah ikut direncanakan. Karena sekali lagi, Lala menganggap percuma buat film bagus tapi promosinya tidak jalan.
Kebijakan Perfilman
Selain sebagai produser dan pendiri LifeLike Pictures, Lala juga menjabat sebagai ketua Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) periode 2013-2016. Sebuah asosiasi yang dibentuk sebagai jawaban atas kebutuhan dan aspirasi para produser film Indonesia untuk ikut memberikan kontribusi pada pengembangan industri film Indonesia dalam berbagai aspek. Mulai dari pemetaan potensi perfilman Indonesia, regulasi kebijakan yang lebih menguntungkan bagi industri film Indonesia, pengembangan kualitas sumber daya manusia, promosi, serta bentu kerjasama-kerjasama internasional yang lebih menguntungkan.
Lantas apa tanggapan Lala terhadap kebijakan perfilman Indonesia sejauh ini? Nyatanya ia mengaku masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Dan sayangnya, Indonesia sendiri tidak memiliki kebijakan yang sejatinya benar-benar pro perfilman Indonesia. “Sebenarnya sudah ada blueprint yang tengah kami perjuangkan di tahun-tahun terakhir ini. Blueprint itulah yang harus diperbaiki. Yakni bahwa film tidak mungkin dapat ditangani oleh dua departemen saja. Harus ada kolaborasi dari seluruh departemen terkait. Apalagi jika kita sudah membicarakan film dalam skema industri. Karena, film sendiri adalah produk yang unik. Film mempertemukan elemen budaya dan ekonomi sekaligus. Ketika kita membicarakan film di tingkat ekonomi, tidak mungkin hanya Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) saja yang terus diandalkan, karena kebijakan soal perekonomian itu ada di Kementerian Perdagangan, juga di Kementerian Perekonomian, ada di Kementerian Keuangan pula.”
Lala juga menambahkan, “Itu yang saya maksud dengan harus ada kolaborasi dari seluruh elemen. Tidak mungkin bisa ditangani oleh satu departemen saja. Contoh lain, tentang undang-undang perfilman yang belum lama ini dibuat. Mengapa kami anggap itu ‘cacat’? Tak lain karena undang-undang tersebut dibuat oleh satu departemen saja. Dan tingkatannya hanya sebatas teori, sementara implementasinya ada di departemen lain di kementerian lain. Yang dibutuhkan sesungguhnya adalah Memorandum of Understanding antar kementerian supaya dapat terjalin kolaborasi yang harmonis. Terlebih, supaya blueprint-nya jelas. Sayang sekali undang-undang kita tumpang tindih satu sama lain. Kemenparekraf membuat undang-undang film, Kemendikbud juga membuat undang-undang film dan undang-undang perihal kesenian. Namun semuanya bertabrakan, tidak ada koordinasi yang jelas antar kementerian satu sama lain. itu masalah utamanya.”
Meskipun masih terbilang baru sebagai asosiasi, APROFI sudah memiliki beberapa pencapaian kecil. Misalnya penandatanganan MOU dengan asosiasi produser film Korea (Producers Guild of Korea), di Busan, Korea Selatan, pada akhir tahun 2014 nanti. Selain untuk membuka peluang koproduksi yang lebih besar, MOU antara Indonesia dan Korea Selatan akan mempermudah terjalinnya kerja sama antar negara. Ini merupakan sebuah langkah yang penting, ujar Lala, karena mencari investor Indonesia untuk film berskala besar masih cukup sulit.
“Namun sebagai ketua, saya selalu menekankan bahwa tidak usah terlalu muluk-muluk. Secara pribadi, saya lebih mengutamakan pada pembuatan fondasi asosiasi yang solid. Tugas kami adalah membereskan konsep yang ingin disampaikan ke pemerintah, mulai dari hal-hal kecil, walaupun kami tetap memberi masukan-masukan seputar riset dan pengembangan lewat Badan Perfilman Indonesia (BPI). Nah, dari situ baru kami ajukan ke pemerintah di periode berikutnya.” imbuh Lala.
Lala berpendapat bahwa langkah-langkah fundamental seperti itulah yang mendesak untuk dibenahi. “Lagipula, kami juga tidak mau terlalu ambisius selama tiga tahun ini. Yang realistis saja lah. Lebih baik begini, agar nanti ketika semuanya sudah rapih, pengurus di masa jabatan mendatang bisa langsung menjalankannya.” sambungnya. Pelan-pelan, sembari membangun fondasi yang kokoh untuk perencanaan jangka panjang.
Kembali ke soal pencarian investor dari dalam negeri, bagi Lala, problem ini sesungguhnya mudah-tidak-mudah. Sebenarnya masih ada banyak celah untuk mendapatkan sumber dana. Bisa dari Pemda, dari donatur, dan lain sebagainya. “Permasalahannya ada di bagian distribusi. Karena investasi tanpa distribusi sebagai langkah pembalikan modal kan sama saja dengan jalur yang macet. Nah, koproduksi itu membuka tidak hanya sekadar investasi saja, namun juga pasar. Dengan adanya koproduksi, kita bisa menjual di dua negara sekaligus. Lebih dari itu, semisal berkoproduksi dengan negara seperti Korea, yang notabene memiliki cengkeraman kuat di festival-festival besar berskala internasional, film-film kita juga akan dibawa serta. Dan tidak terbatas hanya bagi film-film komersil. Film-film art movie sekalipun sangat dimungkinkan. Korea punya pengaruh yang kuat di berbagai festival dunia, seperti Cannes, Toronto, dan banyak lagi. Sedangkan reputasi Indonesia masih belum sampai di tingkat itu.”
Alasan lain adalah karena Korea melihat peluang pemasaran di Indonesia yang sedemikian besar. Dan di sisi lain, secara ekonomis, pemasaran Korea di skala nasional sudah mapan. Oleh karena itu, Korea menjadi perlu mencari peluang-peluang pemasaran lain di luar wilayahnya sendiri. Sebaliknya, Indonesia juga harus cermat menyiasati apa keuntungan yang bisa didapatkan dengan metode kerjasama seperti ini. “Jangan sampai mereka saja yang ekspansi pasar. Tapi kita juga harus cerdik mencari timbal balik apa yang bisa dimanfaatkan.” tutup Lala.
Source: Film Indonesia